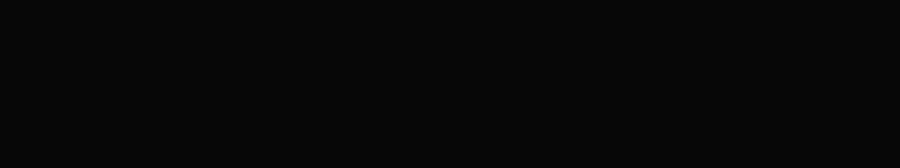harianindonesia.id – Ketika Balatentara Jepang mendarat dan mengambil alih tanah koloni bernama Hindia Belanda pada Maret 1942, banyak tokoh pergerakan nasional senior—yang bercita-cita memerdekakan Indonesia—sudah meninggal dunia. Sebutlah dr. Soetomo (1938), HOS Tjokroaminoto (1934), dan Husni Thamrin (1941).
Setelah Jepang berkuasa, banyak tokoh pergerakan yang dulu melawan pemerintah kolonial makin uzur macam Soewardi Soerjaningrat (yang sudah bersalin nama menjadi Ki Hadjar Dewantara) atau Haji Agus Salim. Jepang mendekati tokoh-tokoh ini dan mengangkatnya sebagai penasihat atau pemimpin organisasi sokongan Jepang. Begitupula tokoh pergerakan seperti Sukarno dan Mohammad Hatta.
Sementara banyak orang yang dulu bekerja sebagai pangreh praja kolonial tetap memegang posisinya. Orang-orang ini disebut golongan tua dan dicap sebagai kolaborator Jepang. Mayoritas dari mereka dilibatkan dalam keanggotaan BPUPKI, yang mengadakan serangkaian perdebatan bagi apa yang dijanjikan Jepang untuk kemerdekaan Indonesia “kelak di kemudian hari.” Termasuk mereka merumuskan UUD 1945.
Sulit menemukan penasihat Jepang dari kalangan komunis atau sosialis yang dulu melawan pemerintah kolonial. Jikapun ada yang terkait dengan Jepang, mereka mau bekerja sebentar untuk sekadar mengelabui intaian mata-mata Jepang.
Wikana, yang antifasis, pernah bekerja di Asrama Indonesia Merdeka yang didirikan Angkatan Laut Jepang pada Oktober 1944. Wikana dan kawan-kawan pemuda, yang tak dapat posisi empuk seperti golongan tua, berperan penting nantinya mendesak Sukarno dan Hatta mempercepat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Di antara tokoh pergerakan di luar BPUPKI, badan bentukan Jepang, ada tiga nama yang bisa kita telusuri aktivitasnya ketika kemerdekaan Indonesia sedang “hamil tua.” Mereka adalah Sjahrir, Amir Sjarifoeddin, dan Tan Malaka.
Di mana Sjahrir?
Sutan Sjahrir memilih tak bekerjasama dengan Jepang. Ia dan orang-orang Indonesia lain percaya bahwa Jepang tak akan menang dalam Perang Pasifik yang disebut kaum fasis sebagai Perang Asia Timur Raya.
Menurut catatan Rudolf Mrazek, Sjahrir: Politics and Exile in Indonesia (1996), Sjahrir berhubungan dengan orang-orang yang dulu bekerjasama dengan Belanda tapi di zaman Jepang tidak bekerja untuk Jepang. Ia berhubungan dengan eks mayor KNIL Soeriosantoso—melalui anak sang mayor, Iwan Santoso yang kuliah kedokteran di Ika Dai Gakko Jakarta. Meski berbeda kepentingan, Jepang adalah musuh mereka. Rumah sang mayor juga menjadi tempat diskusi bagi pemuda antifasis.
Sjahrir juga menjalin kontak dengan De Kadt, politikus Belanda yang “terjebak” di Bandung selama Perang Dunia II. Sjahrir menemuinya karena mendengar De Kadt mengorganisasi gerakan bawah tanah anti-Jepang. Anggotanya pemuda Belanda dan Indo-Belanda. Jaringan penting Sjahrir di daerah-daerah adalah seseorang bernama Sastra, yang rajin mengunjunginya di Sukabumi. Sastra, yang dianggap komunis, dulunya anggota Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru)—yang dipimpin Sjahrir dan Hatta.
Sastra sering bertemu Hatta dan Sjahrir di Jakarta. Mereka berbagi peran. Hatta akan pasang badan paling dekat dengan Jepang. Itu dilakukannya dalam kondisi yang mengharuskanya berkolaborasi, seperti halnya Sukarno.
“Kalau Bung Hatta ditanyai tentang Sjahrir, dia bilang Sjahrir terganggu pikirannya dan agak sinting,” kisah Sastra dalam Mengenang Sjahrir (1980).
Selain dengan Sastra, Sjahrir menghubungi kawan PNI Baru lain. Seperti Rusni di Priangan, Soedarsono, Sugra, dan Sukanda di Cirebon, Wiyono dan Sugiono Yosodiningrat di Yogyakarta, dan Djohan Sjahruzah di Surabaya. Melalui Soejitno, ia berhubungan dengan cendekiawan muda seperti T.B. Simatupang, Ali Budiardjo, dan dr. Abdul Halim. Mereka dekat dengan orang-orang yang bekerja di sumur minyak.Jaringan mantan PNI Baru itu membangun Koperasi Rakyat Indonesia di Jawa Barat, yang disingkat Korindo di Bandung dan KRI di Cirebon.
Amir Lebih Lama di Penjara
Tokoh gerakan bawah tanah lain adalah Amir Sjarifoeddin. Menurut Ken Conboy, Intel: Inside Indonesia’s Intelligence Service (2007), Amir Sjarifoeddin mengaku dirinya bagian dari PKI ilegal belakangan setelah Indonesia merdeka. Namun, di akhir masa kolonial Belanda, Amir adalah pegawai negeri urusan ekonomi.
Pemerintah kolonial tampaknya tahu sepak-terjang Amir dalam pergerakan. Amir adalah pentolan dari Gerindo bersama Muhamad Yamin. Jaringan gerakan bawah tanahnya di era kolonial ingin dimanfaatkan pejabat Belanda macam Charles van der Plas.
“Pengakuan Amir Syarifuddin sendiri—Van der Plas telah memberikan kepadanya F. 25. 000 (dua puluh lima ribu gulden) untuk biaya gerakan di bawah tanah ‘komunis ilegal’ melawan Jepang di Indonesia,” ujar Adam Malik dalam Mengabdi Republik: Angkatan 45 (1978). Uang tak membuat semuanya lancar. Amir yang dikenal tak kenal takut dan suka petualangan itu belakangan hampir nahas melawan Jepang.
Menurut catatan Soe Hok Gie, dalam Orang-orang Di Persimpangan Kiri Jalan (1997), Amir bersekutu dengan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, yang sudah uzur tak lama setelah Jepang datang. Beberapa waktu sebelum Tjipto meninggal dunia pada 1943, mereka membentuk Gerakan Rakyat Anti-Fasis (Geraf). Sayangnya, Geraf dicium intel Jepang. Pembersihan dilakukan sejak awal 1943.
Amir ditangkap pada 30 Januari 1943 oleh Kenpeitai (polisi rahasia Jepang). Hingga Desember 1944, Amir mendekam di penjara Cipinang, Jakarta. Lalu menghuni penjara Kalisosok, Surabaya. Dari Surabaya, pada 17 Desember 1944, Amir dipindahkan ke penjara Lowokmaru, Malang.
Amir hampir dieksekusi pada 19 Februari 1944. Beredar kabar, berkat campur tangan Sukarno dan Hatta, hukuman mati terhadap Amir ditangguhkan. Ia bebas pada Oktober 1945 dan menjadi Menteri Republik.
Tan Malaka Masih Menyamar
Setelah lama berkelana dengan bergonti-ganti identitas, entah di Tiongkok, Filipina, dan daerah lain, demi menghindari kejaran aparat kolonial, Tan Malaka baru kembali ke Indonesia pada 1942.
Dari jazirah Malaya, Tan menyeberang ke Sumatera. Ia lalu menyusuri arah selatan. Setelah tiba di Lampung, ia menuju Jawa. Dengan menumpang perahu layar Sri Renjet dari Lampung, Tan tiba di Banten—Pulau Jawa yang sudah lama tak diinjaknya selama hampir 20 tahun.
Dari Banten, Tan ke Jakarta, menginap di Rawa Jati, dekat Pabrik Sepatu di Kalibata. Tan berusaha menyelami kehidupan rakyat jelata yang jadi buruh atau pedagang buah di pinggiran Jakarta. Mengikuti saran kenalannya, Tan mendatangi Kantor urusan Sosial di Tanah Abang. Ia lalu dapat pekerjaan di Bayah, Banten.
Di sana Tan memakai nama samaran Ilyas Husein dan bekerja di Bayah Kozan, salah satu bagian dari perusahaan Jepang Sumitomo. Ia sempat jadi juru tulis di pergudangan lalu pindah ke bagian yang mengurusi administrasi para romusha.
Setelah BPUPKI bekerja mempersiapkan apa yang harus dimiliki sebuah negara baru, pada 6 Agustus 1945, “Tan Malaka pergi ke Jakarta,” tulis Harry Poeze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid I (2008).
Tan hanya beberapa hari di Jakarta, menemui pemuda macam Chaerul Saleh maupun Baharudin Mohamad Diah, kemudian kembali ke Bayah.
Minggu-minggu tersebut adalah minggu-minggu yang sibuk bagi pemuda-pemuda di Jakarta, baik yang berhubungan dengan Tan Malaka dan Sjahrir. Banyak orang dalam jaringan Sjahrir, Tan, juga Amir, yang sudah ditahan, yang menyimpan radio.
Dari radio pula mereka tahu Jepang sudah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di atas kapal USS Missouri pada 14 Agustus 1945. Setelah berita itu, di bawah komando Wikana, pemuda-pemuda mendesak golongan tua macam Sukarno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Meski berjalan alot, Sukarno-Hatta akhirnya mau mendengarkan desakan kaum muda. Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada 17 Agustus 1945.
Menurut Hatta dalam Bung Hatta Menjawab (1978), seandainya pada 15 Agustus 1945 para pemuda tidak menculik Sukarno dan dirinya, yang saat itu sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI, kemungkinan besar proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di gedung Pejambon, bukan di rumah Sukarno, Jalan Pegangsaan Timur No.56.
Sumber: tirto.co.id